By : Agus Setiawan, Fakultas Syari’ah, Semester VI
Pokja Pengarusutamaan Gender, Departemen Agama RI
Pengantar
Hasil-hasil penelitian baik berupa tesis maupun disertasi menyatakan bahwa KHI memiliki kelemahan pokok justru pada rumusan visi dan misinya. Terang benderang, beberapa pasal di dalam KHI secara prinsipil berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang universal, seperti prinsip persamaan (al-musâwah), persaudaraan (al-ikhâ`), dan keadilan (al-`adl), serta gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat madani, seperti pluralisme, kesetaraan gender, HAM, demokrasi, dan egalitarianisme.
KHI dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional Eksistensi hukum Islam di Indonesia selalu mengambil dua bentuk; hukum normatif yang diimplementasikan secara sadar oleh umat Islam, dan hukum formal yang dilegislasikan sebagai hukum positif bagi umat Islam. Yang pertama menggunakan pendekatan kultural, sementara yang kedua menggunakan penghampiran struktural. Hukum Islam dalam bentuk kedua itu pun proses legislasinya menggunakan dua cara. Pertama, hukum Islam dilegislasikan secara formal untuk umat Islam, seperti PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan, UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
KHI dan Konteks Politik Hukum
Telah maklum bahwa KHI lahir bukan dari kondisi yang vakum. Ada kondisi-kondisi sosial, politik, dan hukum yang mendorong KHI harus lahir. KHI lahir dari rahim negara. Ia lahir sebagai produk politik negara Orde Baru, yang jika dipandang dari optik politik hukum tentu saja tidak bebas nilai dan tidak bebas kuasa dari muatan interest politik rezim itu. Dengan perkataan lain, pembidanan kelahiran dan keberadaan KHI terselimuti oleh bias-bias kekuasaan rezim Orde Baru. Setiap legislasi oleh negara, apalagi negara Orde Baru yang saat itu berwatak otoritarian-birokratik, terdapat suatu kehendak-kehendak sosial politik tersembunyi yang menyertainya, sebagaimana anutan banyak pakar hukum bahwa tak ada hukum yang bebas nilai, bebas kepentingan, dan bebas kuasa. Termasuk dalam jaring-jaring ini adalah hukum Islam yang terkumpulkan dalam KHI, kehadirannya menjadi sarat dengan nilai, kepentingan, dan relasi kuasa. Dengan nalar demikian, wajar kiranya kalau KHI dipandang oleh sebagian orang sebagai “fikih madzhab negara”. Ini karena elemen-elemen konstruksi hukum Islam dalam KHI mulai dari inisiatif, proses penelitian, penyusunan, hingga penyimpulan terakhir dari pilihan-pilihan hukumnya semuanya dilakukan oleh suatu tim yang beranggotakan hampir seluruhnya orang-orang negara. Betapa latar belakang pembentukan, logika hukum yang digunakan, hingga pola redaksi yang diterapkan juga sebagaimana lazimnya digunakan oleh hukum positif negara. Bahkan, legitimasi hukum pemberlakuannya juga sangat bergantung pada keputusan negara melalui Instruksi Presiden.
Berdasarkan kajian politik hukum, KHI setidak-tidaknya memiliki 4 (empat) buah karakter hukum yang spesifik sebagai akibat logis dari pengaruh politik hukum pada masanya. Karakter-karakter tersebut adalah sebagai berikut:
[1] dari perspektif strategi pembentukan hukum, KHI berkarakter semi-responsif, yakni proses pembentukannya dikuasai oleh pihak yudikatif (MA) dan eksekutif (Depag RI), sementara pihak legislative (DPR) selaku perwakilan-formal rakyat Indonesia tidak terlibat sama sekali dan perwakilan masyarakat Islam (MUI dan cendekiawan Muslim di IAIN) berada pada posisi peripheral; [2] dari perspektif materi hukum, KHI berkarakter otonom, reduksionistik dan konservatif.
KHI dalam Perbandingan Hukum Keluarga Negeri-Negeri Muslim
Kiranya penting juga untuk menjuktaposisikan KHI dengan hukum keluarga (the family law) yang ada di berbagai negeri Islam yang lain. Negeri-negeri Muslim tersebut telah berkali-kali mengadakan sejumlah pembaharuan terhadap hukum keluarga.
TUNISIA
Tunisia adalah sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Tunisia merdeka pada tanggal 20 Maret 1956. Sesaat setelah itu, Pemerintah Tunisia telah membuat undang-undang hukum keluarga yang bernama Majallah al-Ahwâl al-Syakhshiyyah Nomor 66 Tahun 1956. Semenjak ditetapkan, Majallah tersebut telah berkali-kali mengalami perubahan, penambahan, modifikasi, yaitu pada tahun 1959, 1964, 1981, dan 1993. UU tersebut mencakup materi hukum perkawinan, perceraian, dan pemeliharaan anak yang dari segi material berbeda dengan ketetapan fikih klasik. Dari sekian banyak pembaharuan terhadap UU tersebut, pada tahun 1959 telah ditetapkan tentang keharusan perceraian di pengadilan dan larangan untuk berpoligami. Sementara itu, menyangkut anak angkat atau adopsi telah diatur secara khusus dalam UU Perwalian dan Adopsi tahun 1958. UU ini terdiri dari 60 pasal yang dibagi ke dalam 3 bab, yaitu mengenai perwalian umum, kafalah, dan anak angkat. Dalam pasal 9-16, misalnya disebutkan bahwa pihak yang akan mengadopsi anak disyaratkan sudah dewasa, menikah, memiliki hak-hak sipil secara penuh, bermoral baik, sehat jasmani dan rohani, dan secara finansial mampu memenuhi kebutuhan anak yang diadopsi. Selain itu, selisih umur antara pihak yang mengadopsi dan yang diadopsi adalah 15 tahun. Di dalam keluarga angkatnya, anak angkat memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagaimana anak kandung.
SYRIA
Menyangkut hukum keluarga, Syiria telah memiliki Qanûn al-Ahwâl al-Syakhshiyyah tahun 1953. Setelah berlaku selama 22 tahun, undang-undang ini kemudian diamandemen menjadi UU Nomor 34 tahun 1975 dengan maksud untuk menjamin hakhak perempuan dalam pandangan hukum Islam. Sebelum diamademen, berkenaan dengan poligami UU tersebut (pasal 17) menyatakan demikian, “hak poligami bagi suami diperbolehkan asalkan suami dapat membuktikan bahwa ia mampu untuk memberi hidup kepada isteri”. Setelah diamandemen, pasal poligami itu berbunyi, “Pengadilan bisa saja tidak memberikan izin untuk poligami kecuali ada justifikasi hukum untuk poligami dan mampu membiayai dua isteri”. Dengan mempersyaratkan perizinan dari pihak pengadilan, maka sedikitnya telah memperpanjang dan mempersulit proses
poligami. Sementara itu, masalah perceraian merupakan persoalan menarik dalam hukum keluarga Syiria karena terkait dengan hak isteri untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya melalui jalur khulu’. Selain melalui khulu’, isteri dapat pula mengajukan pemutusan hubungan perkawinan kepada pengadilan disebabkan kasuskasus antara lain: suami menderita penyakit yang dapat menghalangi untuk hidup bersama, penyakit gila dari suami, suami meninggalkan isteri atau dipenjara lebih dari tiga tahun, suami dianggap gagal memberikan nafkah, dan penganiayaan suami terhadap isteri.
MESIR
Secara historis, pembaharuan hukum keluarga di Mesir dimulai sekitar tahun 1920. Pada tahun ini, seri pertama rancangan undang-undang hukum keluarga resmi diundangkan. Pada tahun 1929 dilakukan amandemen kedua terhadap beberapa pasal pada undang-undang sebelumnya. Setelah itu, tercatat dua kali amandemen terhadap hukum keluarga Mesir yaitu pada tahun 1979 dan 1985. Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Mesir antara lain terkait dengan masalah poligami, wasiat wajibah, warisan, dan pengasuhan anak. UU Nomor 100 tahun 1985 menyatakan bahwa seorang yang akan menikah harus menjelaskan status perkawinannya pada formulir pencatatan perkawinan. Bagi yang sudah mempunyai isteri, harus mencantumkan nama dan alamat isteri atau isteri isterinya. Pegawai pencatat harus memberitahu isterinya tentang rencana perkawinan tersebut. Seorang isteri yang suaminya menikah lagi dengan perempuan lain dapat minta cerai dengan berdasarkan kemudharatan ekonomi yang diakibatkan poligami dan mengakibatkan tidak mungkin hidup bersama dengan suaminya. Hak isteri untuk minta cerai hilang dengan sendirinya ketika yang bersangkutan tidak memintanya selama satu tahun setelah ia mengetahui perkawinan tersebut. Bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan atau denda 200 Pound Mesir atau kedua-duanya.
YORDANIA
Sampai tahun 1951, Yordania masih memberlakukan hukum keluarga Turki Usmani sampai diundangkannya undang-undang hak-hak keluarga Nomor 92 Tahun 1951. Undang-Undang ini mengatur tentang perkawinan, perceraian, mahar, pemenuhan nafkah bagi isteri dan keluarga, dan tentang pemeliharaan anak. Pada perkembangan berikutnya, UU tersebut telah diganti dengan status personal Yordan 1976 (UU Nomor 61 Tahun 1976) yang disebut dengan Qanûn al-Ahwâl al-Syakhshiyyah. Amandemen berikutnya terjadi pada tahun 1977 yang menghasilkan UU Nomor 25 Tahun 1977. Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Yordania antara lain terkait dengan masalah usia menikah, janji pernikahan, perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan, perceraian, dan wasiat wajibah. Mengenai usia pernikahan dinyatakan bahwa syarat usia perkawinan adalah 17 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Apabila perempuan telah mencapai usia 15 tahun dan mempunyai keinginan untuk menikah sementara walinya tidak mengijinkan tanpa alasan yang sah, maka perempuan tersebut pada dasarnya tidak melanggar prinsip-prinsip kafâ`ah dan pengadilan dapat memberikan ijin pernikahan. Demikian juga apabila perempuan telah mencapai umur 18 tahun dan walinya keberatan memberikan izin tanpa alasan kuat, maka pengadilan dapat memberi izin pernikahan. Sementara itu, janji untuk mengadakan pernikahan diatur pada pasal 2 dan 3 UU Tahun 1951. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa janji menikah tidak akan membawa akibat pada adanya pernikahan. Namun, setelah adanya perjanjian, kemudian salah satunya meninggal atau perjanjian batal, maka beberapa hadiah sebelumnya dapat diambil kembali oleh pihak laki-laki.
IRAK
Irak pernah memiliki Qanûn al-Ahwâl al-Syakhshiyyah yang mengatur masalah keluarga. Undang-undang ini secara resmi diumumkan pada Bulan Desember 1959. Prinsip prinsip tentang masalah keluarga dalam undang-undang ini diambil dari berbagai madzhab dalam Islam yang meliputi Sunni, Syi’ah, dan juga hukum keluarga yang berlaku di beberapa negeri Muslim seperti Mesir, Yordania, dan Syiria. Perundangundangan tersebut kemudian diamandemen pada tahun 1963, 1978, dan 1983. Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Irak antara lain terkait dengan masalah status wali, pemberian mahar, wasiat wajibah, dan pengasuhan anak (hadhânah). Pasal 19-22 mengatur tentang ketentuan pembayaran mahar. Pasal-pasal ini menjelaskan bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan mahar yang ditetapkan secara khusus di dalam perjanjian perkawinan. Jika mahar tidak ditetapkan secara khusus, maka perempuan berhak menerima mahar yang pantas (mahar mitsil). Jika pihak yang lain menggagalkan perkawinan atau meninggal dunia, maka harta yang telah diberikan harus dikembalikan secara utuh. Sementara mengenai masalah pengasuhan anak di atur dalam pasal 57 ayat 1-9. Secara panjang lebar dijelaskan antara lain bahwa ibu memiliki hak istimewa dalam mengasuh dan mendidik anak selama perkawinan berlangsung. Begitu juga setelah perkawinan, dengan catatan ia tidak berbuat aniaya terhadap anak tersebut. Pengasuh tersebut harus dewasa, sehat, dapat dipercaya dan mampu bertanggungjawab dan melindungi anaknya serta tidak kawin lagi dengan lelaki asing.
KHI dalam Lingkup Problematika sosial
Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yang antara lain membawa kepada perubahan pola interaksi manusia, sejumlah problem sosial muncul. Problem-problem ini pada umumnya tidak terwadahi secara memadai dalam KHI. Problem sosial yang dimaksud adalah persoalan ketidakadilan, ketidakmanusiawian, dan diskriminasi yang ditemukan terutama dalam dua materi pokok KHI, yaitu hukum perkawinan dan hukum kewarisan.
Kedua, tentang wali nikah. Pembahasan tentang wali nikah dijelaskan dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Di antara pasal-pasal tersebut, yang cenderung bias jender adalah pasal 19, 20 ayat (1) dan 21 ayat (1). Hak kewalian hanya dimiliki oleh orang yang berkelamin laki-laki. Tidak ada ruang sedikitpun bagi seorang ibu untuk menjadi wali nikah atas anak perempuannya, misalnya ketika sang ayah berhalangan. Sekiranya ayah tidak memungkinkan untuk tampil menjadi wali, maka hak kewalian jatuh pada kakek. Jika kakek ‘udzur, maka hak kewalian tidak secara otomatis pindah ke tangan ibu, tetapi turun pada anak laki-laki atau saudara laki-laki kandung dari si perempuan tersebut. Hirarki kewalian ini telah diatur oleh KHI dalam pasal 21 dengan menutup sama sekali peluang perempuan untuk menjadi wali. Untuk itu, secara praktis harus ditegaskan bahwa pasal tentang perwalian dalam KHI hendaknya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki memiliki otoritas untuk menikahkan dirinya sendiri dan berwenang menjadi wali nikah, maka seharusnya demikian juga untuk perempuan.
Ketiga, tentang saksi. Ketentuan tentang saksi dalam pernikahan diatur dalam pasal 24,25, dan 26. Namun, yang dinilai bias jender hanyalah pasal 25 saja yang menutup sama sekali kemungkinan perempuan untuk menjadi saksi pernikahan. Dengan menggunakan parameter kesetaraan gender, maka semestinya laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk tampil sebagai saksi nikah.
Kelima, pengaturan tentang nusyûz dalam KHI terdapat dalam pasal 84 ayat (1). Namun demikian, dalam persoalan nusyûz ini KHI masih terlihat bias jender. Sebab, masalah nusyûz dalam KHI hanya berlaku bagi pihak perempuan, sementara laki-laki (baca: suami) yang mangkir dari tanggungjawabnya tidak diatur dan tidak dianggap nusyûz. Oleh sebab itu, pasal ini terlihat mengekang kebebasan hak-hak perempuan dan tidak mendudukkan hubungan suami isteri secara setara.
Keenam, pemberian mahar dari seorang suami terhadap isteri. Pertanyaannya, bukankah dengan mahar ini, laki-laki (suami) semakin digdaya di hadapan perempuan (isteri). Terdapat anggapan yang menggumpal di alam bawah sadar seorang suami bahwa dirinya telah “membeli” (alat kelamin, vagina) isteri, sehingga dapat dengan leluasa memperlakukannya. Transaksi “pembelian” melalui selubung mahar ini akan terungkap dengan jelas ketika membaca pasal 35 ayat 1 yang berbunyi, “suami yang mentalak isterinya qabla al-dukhûl wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Dalam fikih, walau masih diperdebatkan, ada pendapat yang menyatakan bahwa hak suami terhadap isteri adalah haqq al-tamlîk dan bukan haq al-intifâ.
Ketujuh, poligami. Dalam KHI poligami masih dimungkinkan untuk dilakukan. Pandangan ini seperti ini dapat disangkal dengan dua alasan berikut: [1] asas perkawinan dalam Islam adalah monogami dan bukan poligami. Oleh karena itu, perkawinan poligami jelas bertentangan dengan asas tersebut. [2] Perkawinan poligami dalam prakteknya sangat menyakitkan bagi istri. Beberapa penelitian menemukan sebuah fakta bahwa sebagian besar perkawinan poligami diselenggarakan secara sembunyisembunyi tanpa sepengetahuan dan seijin istri. Dengan fakta ini, maka tindak kebohongan yang begitu menyakitkan telah terjadi. Kejujuran dan keterbukaan yang semestinya menjadi landasan utama dalam rumah tangga kemudian menjadi rapuh.
Kedelapan, nikah beda agama. Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi sepasang pemuda dan pemudi yang hendak melangsungkan suatu perkawinan. Artinya, orang Islam baik laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang non-Islam. Pandangan seperti ini tentu saja bertentangan prinsip dasar ajaran Islam, yaitu pluralisme. Dengan berlandas tumpu pada nalar pluralisme itu, maka tidak tepat menjadikan perbedaan agama (ikhtilâf ad-dîn) sebagai penghalang (mâni’) bagi dilangsungkannya suatu perkawinan beda agama. Selain ketidakadilan pada hukum perkawinan, KHI juga tidak mencerminkan keadilan pada hukum kewarisan. Dalam hukum kewarisan, ketentuan-ketentuan hukum KHI tampak mengabaikan hak-hak anak yang sedang dalam kandungan. KHI hanya memperhitungkan bagian anak yang telah lahir. Padahal, anak yang sedang dalam kandungan justru memiliki beban yang lebih berat, baik dari aspek psikologis maupun finansial. Oleh karena itu, sudah selayaknya KHI merumuskan konsep tentang pembagian warisan bagi anak yang sedang dalam kandungan.
Ketidakadilan lain terlihat pada pasal 172 KHI yang diantaranya menyatakan bahwa bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Secara implisit, pasal ini menyatakan bahwa agama ibu tidak bernilai sama sekali pada anaknya, baik dalam pandangan masyarakat maupun dalam pandangan Tuhan. Padahal, posisi ibu dalam keluarga sangat penting sebagai pendidik dan perambah masa depan anak-anaknya. Ini tidak saja mengabaikan peran dan posisi ibu dalam keluarga dan amsyarakat, tetapi juga menafikan agama yang dianut ibu di hadapan anak-anaknya.
Hal senada juga terjadi pada pasal 186 KHI. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan kelaurga dari pihak ibunya. Sementara status anak yang lahir karena kawin sirri tidak diatur dalam kaitan dengan hubungan kewarisan. Oleh karena itu, definisi sah atau tidaknya perkawinan kiranya penting untuk ditinjau kembali.
Di samping nuansa ketidakadilan, hukum kewarisan juga memuat beberapa kendala teknis yang dirasakan sulit dalam penerapannya. Kendala teknis itu, antara lain, terdapat pada pasal 192 dan 193 yang tidak menjelaskan secara eksplisit mana yang ‘awl dan mana pula yang radd. Jika tidak segera dijelaskan tentu saja akan menyulitkan para hakim di pengadilan untuk menyelesaikan persoalan warisan keluarga Muslim. Kendala teknis lain terdapat pada Bab V dan bab VI yang tidak menjelaskan secara rinci definisi wasiat dan hibah. Pendefinisian dua terminologi ini cukup penting karena adanya kemiripan dalam praktik wasiat dan hibah.
Sedangkan dari sisi hukum wakaf, KHI juga belum dapat dikatakan sempurna mengingat masih banyak persoalan penting yang belum terakomodasi. Di antara persoalan tersebut adalah ketentuan wakaf non-Muslim perlu mendapat tempat dalam KHI mengingat adanya beberapa kasus yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya hal tersebut. Aturan itu setidaknya dapat menegaskan boleh tidaknya warga non-Muslim untuk mewakafkan harta bendanya untuk kepentingan umat Islam. Aturan tentang wakaf tunai juga perlu diakomodasikan dalam KHI.
Dalam banyak kajian akademis, KHI tidak digali sepenuhnya dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan banyak “mengangkut” begitu saja penjelasan normatif tafsirtafsir keagamaan klasik, dan kurang mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat Islam Indonesia. KHI mengutip nyaris sempurna seluruh pandangan-pandangan fikih “purba”. KHI tidak betul-betul merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam Indonesia, akibat tidak digali secara seksama dari kearifan-kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendeknya, telah terjadi sakralisasi fikih klasik yang kita yakini para penulisnya sendiri tidak menginginkan hal itu.
Sejumlah pemikir Islam telah menilai beberapa sisi ketidakrelevanan fikih-fikih klasik itu, oleh karena ia memang disusun dalam era, kultur dan imajinasi sosial yang berbeda. Bahkan, disinyalir bahwa fikih klasik tersebut bukan saja tidak relevan dari sudut materialnya, melainkan juga bermasalah dari ranah metodologisnya. Misalnya, per definisi fikih selalu dipahami sebagai “mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil tafshili, yaitu al-Qur`an dan al-Sunnah” [al-‘ilmu bi al-ahkâm al-syar’iyyah al-‘amaliyyah al-muktasab min adillatihâ al-tafshîliyyah]. Mengacu pada ta’rîf tersebut, kebenaran fikih menjadi sangat normatif, sehingga kebenaran fikih bukan dimatriks dari seberapa jauh ia memantulkan kemaslahtan bagi umat manusia, melainkan pada seberapa jauh ia benar dari aspek perujukannya pada aksara al-Qur`an dan al-Sunnah.
Metodologi dan pandangan literalistik ini belakangan terus mendapatkan pengukuhan dari kalangan Islam fundamentalis-idealis. Mereka selalu berupaya untuk menundukkan realitas ke dalam kebenaran dogmatik nash, dengan pengabaian yang nyaris sempurna terhadap kenyataan konkret di lapangan. Bahkan, seringkali terjadi, mereka telah melakukan tindakan eisegese, yakni membawa masuk pikiran atau ideologinya sendiri ke dalam nash, lalu menariknya ke luar dan mengklaimnya sebagai maksud Tuhan. Klaim kebenaran ini sangat berbahaya. Ia hanya akan membuat umat Islam menjadi semakin eksklusif dalam tata pergaulan yang multireligius dan multikultural. Telah terbukti, klaim-klaim seperti itu tidak memberikan pengaruh positif apapun dalam usaha-usaha membangun kehidupan bersama yang toleran dalam masyarakat yang mejemuk.
Dari fondasi paradigmatik ini kita dapat merencanakan beberapa kaidah ushul fikih alternatif, misalnya, pertama, adalah kaidah al-ibrah bi al-maqâshid la bi al alfadz. Kaidah ini berarti bahwa yang mesti menjadi perhatian seorang mujtahid di dalam mengistinbatkan hukum dari al-Qur`an dan al-Sunnah bukan huruf dan aksaran al- Qur`an dan al-Hadits melainkan dari maqâshid yang dikandungnya. Yang menjadi aksis adalah cita-cita etik-moral dari sebuah ayat dan bukan legislasi spesifik atau formulasi literalnya. Nah, untuk mengetahui maqâshid ini maka seseorang dituntut untuk memahami konteks. Yang dimaksudkan bukan hanya konteks personal yang juz`iy-partikular melainkan juga konteks impersonal yang kulli-universal. Pemahaman tentang konteks yang lebih dari sekadar ilmu sabab al-nuzul dalam pengertian klasik itu merupakan prasyarat utama untuk menemukan maqâshid al-syarî’ah. Kedua, adalah kaidah jawaz naskh al-nushush bi al maslahah.
Ketiga, adalah kaidah tanqih al nuhush bi al-‘aql al-mujtama’. Kaidah ini hendak menyatakan bahwa akal publik memiliki kewenangan untuk menyulih dan mengamandemen sejumlah ketentuan “dogmatik” agama menyangkut perkaraperkara publik. Sehingga ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan bunyi harfiah teks ajaran, maka akal publik berotoritas untuk mengedit, menyempurnakan, dan memodifikasikannya.
Menyusun Visi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia
Bertolak dari beberapa problem di atas, maka ke depan KHI diharapkan dapat mencerminkan visi dan landasan berikut:
1. Pluralisme (al-Ta’addudiyyah).
Tak terbantahkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat plural. Pluralitas initerjadi bukan hanya dari sudut etnis, ras, budaya, dan bahasa melainkan juga agama. Sehingga, kemajemukan di Indonesia tidak mungkin bisa dihindari. Keberagaman telah menyusup dan menyangkut dalam pelbagai ruang kehidupan. Tidak saja dalam ruang lingkup keluarga besar seperti masyarakat negara, bahkan dalam lingkup keluarga, pluralitas juga bisa berlangsung. Setiap orang senantiasa berada dalam dunia pluralitas.
Menghadapi pluralitas tersebut, yang dibutuhkan tentu saja bukan pada bagaimana menjauhkan diri dari kenyataan pluralisme tersebut, tetapi pada bagaimana cara dan mekanisme yang bisa diambil di dalam menyikapi pluralitas itu. Sikap antipati terhadap pluralitas, di samping bukan merupakan tindakan yang cukup tepat, juga akan berdampak kontra-produktif bagi tatanan kehidupan manusia yang damai.
2. Nasionalitas (Muwâthanah).
Telah maklum bahwa sebagai sebuah negara, Indonesia dibangun bukan oleh satu komunitas agama saja. Indonesia merekrut anggotanya bukan didasarkan pada kriteria keagamaan, tetapi pada nasionalitas. Dengan perkataan lain, yang menemalikan seluruh warga negara Indonesia bukanlah basis keagamaan, melainkan basis nasionalitas (muwâthanah). Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil jerih payah seluruh warga bangsa, bukan hanya masyarakat Islam melainkan juga non Islam, bukan hanya masyarakat Jawa melainkan juga masyarakat luar Jawa.
3. Penegakan HAM (Iqâmat al-Huqûq al-Insâniyyah).
Hak asasi manusia dimaksudkan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia karena terberikan kepadanya. Hak asasi mengungkapkan segi-segi kemanusiaan yang perlu dilindungi dan dijamin dalam rangka memartabatkan dan menghormati eksistensi manusia secara utuh. Oleh karena manusia dengan martabatnya merupakan ciptaan Allah, maka dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia dimiliki manusia karena diberikan oleh Allah sendiri. Dengan demikian, hak asasi manusia secara otomatis akan dimiliki oleh setiap insan yang lahir di bumi ini.
Islam adalah agama yang memiliki komitmen dan perhatian cukup kuat bagi tegaknya hak asasi manusia di tengah masyarakat. Dalam sejarahnya yang awal, Islam hadir justru untuk menegakkan hak asasi manusia, terutama hak kaum mustadh’afîn, yang banyak dirampas oleh para penguasa. Misalnya, Islam datang untuk mengembalikan hak-hak kaum perempuan, para budak, dan kaum miskin. Mereka inilah kelompokkelompok yang rentan kehilangan haknya yang paling asasi sekalipun. Dalam Islam, ada sejumlah hak asasi manusia yang harus diusahakan pemenuhannya, baik oleh diri sendiri maupun negara. Masing-masing adalah hak hidup (hifdz al-nafs aw al-hayât), hak kebebasan beragama (hifdz al-dîn), hak kebebasan berfikir (hifdz al-‘aql), hak properti (hifdz al-mâl), hak untuk mempertahankan nama baik (hifdz al-‘irdh), dan hak untuk memiliki garis keturunan (hifdz al-nasl). Menurut al-Ghazali, pada komitmen untuk melindungi hak-hak kemanusiaan inilah, seluruh ketentuan hukum dalam Islam diacukan.
4. Demokratis.
Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik, secara mendasar bisa dikatakan paralel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Artinya, pada dataran prinsipil tersebut antara Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan. Sejumlah konsep ajaran Islam yang dipandang sejalan dengan prinsip demokrasi adalah; pertama, al-musâwah (egalitarianism). Bahwa manusia memiliki derajat dan posisi yang setara di hadapan Allah. Kedua, al-hurriyah (kemerdekaan). Ketiga, al-ukhuwwah (persaudaraan). Keempat, al-‘adâlah (keadilan) yang berintikan pada pemenuhan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat-negara. Kelima, al-syûra (musyawarah). Bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartsipasi di dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama.
Kiranya mekanisme penyusunan sebuah kompilasi hukum Islam harus bersendikan kelima pokok ajaran tersebut.
5. Kemaslahatan (al-mashlahat).
Sesungguhnya syari’at (hukum) Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (jalb al-mashâlih) dan menolak segala bentuk kemafsadatan (dar`u al-mafâsid). Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, seorang tokoh Islam bermadzhab Hanbali, menyimpulkan bahwa syari’at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan (al-mashlahat), keadilan (al-’adl), kerahmatan (al-rahmat), dan kebijaksanaan (al-hikmah). Prinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran para ahli fikih ketika memutuskan suatu kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsipini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam. Persoalannya, jika acuan hukum adalah kemaslahatan, maka siapa yang berhak mendefinisikan dan yang memiliki otoritas untuk merumuskannya. Untuk menjawabnya, perlu kiranya dibedakan antara kemaslahatan yang bersifat individualsubyektif dan kemashlahatan yang bersifat sosial-obyektif. Yang pertama adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang per orang yang terpisah dengan kepentingan orang lain. Tentu saja sebagai penentu kemaslahatan pertama ini adalah yang bersangkutan itu sendiri, seperti dalam kasus poligami (perempuanlah penentu kemaslahatan dan keadilan).
Sedangkan jenis kemaslahatan kedua adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, otoritas yang memberikan penilaian adalah orang banyak juga melalui mekanisme syûra untuk mencapai konsensus (ijmâ’). Dan sesuatu yang telah menjadi konsensus dari proses pendefinisian maslahat melalui musyawarah itulah hukum tertinggi yang mengikat kita. Di sinilah pemecahan masalah bersama cukup menentukan. Al-Qur`an mengatakan, urusan mereka dimusyawarahkan (dibicarakan dan diputuskan) bersama di antara mereka sendiri. (QS.: al-Syûrâ, 38).
6. Kesetaraan Gender (al-‘Musâwah al-Jinsiyyah).
Gender dan seks merupakan dua entitas yang berbeda. Jika gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosialbudaya, maka seks secara umum dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Artinya, gender bukan kategori biologis yang berkaitan dengan hitungan kromosom, pola genetik, struktur genital, melainkan merupakan konstruksi sosial dan budaya. Sementara seks merupakan kodrat Tuhan bersifat permanen.
Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang perlu dipersoalkan. Tidak mengapa bahwa karena kodratnya, perempuan harus melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Problem baru muncul tatkala perbedaan jenis kelamin tersebut melahirkan ketidakadilan perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan diposisikan sebagai makhluk yang hanya boleh bekerja dalam dunia domestik dan tidak dalam dunia publik karena dunia publik merupakan area khusus bagi laki-laki. Perempuan tidak memiliki kewenangan untuk menjadi pemimpin di tingkat keluarga maupun masyarakat.
Di sinilah letak pentingnya memisahkan seks dan gender secara proporsional. Dari sudut gender, relasi antara laki-laki dan perempuan mesti diletakkan dalam konteks kesetaraan dan keadilan. Sebab, ketidakadilan gender di samping bertentangan dengan spirit Islam, juga hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan. Islam dengan sangat tegas telah mengatakan bahwa laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Yang membedakan di antara mereka hanyalah kadar ketakwaannya saja.
Pokok-pokok pikiran ini adalah dasar dan acuan dari kerja pembaharuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Semoga berguna dan bermanfaat. In urîdu illa al-ishlâh mastatha’tu. Wa mâ tawfîqiy illâ billâh.@
****
Pokja Pengarusutamaan Gender, Departemen Agama RI
Pengantar
Sejumlah kajian dan penelitian menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung dalam dirinya berbagai potensi kritik. Kritik umumnya diarahkan selain pada eksistensi KHI juga pada substansi hukumnya yang dipandang tidak lagi memadai dalam menyelesaikan pelbagai problem keumatan yang cukup kompleks. Ini karena konstruksi KHI sejak awal kelahirannya telah membawa pelbagai kelemahan.
Hasil-hasil penelitian baik berupa tesis maupun disertasi menyatakan bahwa KHI memiliki kelemahan pokok justru pada rumusan visi dan misinya. Terang benderang, beberapa pasal di dalam KHI secara prinsipil berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang universal, seperti prinsip persamaan (al-musâwah), persaudaraan (al-ikhâ`), dan keadilan (al-`adl), serta gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat madani, seperti pluralisme, kesetaraan gender, HAM, demokrasi, dan egalitarianisme.
Di samping itu juga disinyalir oleh para pakar hukum, di dalam KHI terdapat sejumlah ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan hukum-hukum nasional dan konvensi internasional yang telah disepakati bersama. Belum lagi kalau ditelaah dari sudut metodologi, corak hukum KHI masih mengesankan replika hukum dari produk fikih jerih payah ulama zaman lampau di seberang sana. Konstruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, melainkan lebih mencerminkan penyesuaian-penyesuaian dari fikih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya. Program ini hadir untuk membaca ulang KHI setelah 12 tahun berlalu dan menyusunnya kembali dalam perspektif baru (meliputi visi dan misi) yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini.
KHI yang diharapkan adalah seperangkat ketentuan hukum Islam yang senantiasa menjadi rujukan dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Semua ketentuan tersebut hendak digali dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, al-Qur’ân dan al-Sunnah, melalui pengkajian terhadap kebutuhan, pengalaman, dan ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khazanah intelektual klasik Islam, dan pengalaman peradaban masyarakat Muslim dan Barat di belahan dunia yang lain.
KHI dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional Eksistensi hukum Islam di Indonesia selalu mengambil dua bentuk; hukum normatif yang diimplementasikan secara sadar oleh umat Islam, dan hukum formal yang dilegislasikan sebagai hukum positif bagi umat Islam. Yang pertama menggunakan pendekatan kultural, sementara yang kedua menggunakan penghampiran struktural. Hukum Islam dalam bentuk kedua itu pun proses legislasinya menggunakan dua cara. Pertama, hukum Islam dilegislasikan secara formal untuk umat Islam, seperti PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan, UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Kedua, materimateri hukum Islam diintegrasikan ke dalam hukum nasional tanpa menyebutkan hukum Islam secara formal, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berbeda dengan itu, KHI dalam sejarahnya adalah produk kebijakan hukum pemerintah yang proses penyusunannya didasarkan pada hukum normatif Islam, terutama fikih madzhab Syafi’i. Oleh karenanya, boleh jadi hal itu membuat KHI tampil dalam wajah yang tidak akrab dengan hukum-hukum nasional dan internasional yang memiliki komitmen kuat pada tegaknya masyarakat yang egaliter, pluralis, dan demokratis. Bahkan disinyalir oleh sejumlah pemikir Muslim bahwa alih-alih menjadi landasan agama untuk demokratisasi, KHI sendiri dalam beberapa pasalnya mengandung potensi sebagai penghambat laju gerak demokrasi di Indonesia.
Kalau pasal-pasal tersebut tetap dibiarkan, maka KHI akan terus menerus turut menyuburkan praktik diskriminasi dalam masyarakat, terutama terhadap perempuan dan kaum minoritas. Tentu saja praktik ini bertentangan dengan produk-produk hukum nasional, seperti UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Undang-Undang yang terakhir ini dirumuskan sebagai konsekuensi logis dari ratifikasi negara terhadap CEDAW (The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap perempuan, bahkan dengan UUD 1945 dan Amandemen UUD 1945.
Dalam hal-hal tertentu, praktik diskriminasi juga berseberangan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pada prinsip desentralisasi dengan ciri partisipasi seluruh masyarakat tanpa membedakan laki dan perempuan. Pada tataran internasional, terdapat sejumlah instrumen penegakan dan perlindungan HAM, antara lain Deklarasi Universal HAM (1948), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966), CEDAW (1979), Deklarasi Kairo (1990), dan Deklarasi dan Program Aksi Wina (1993). Sebagai dampak ikutan dari kesepakatankesepakatan tersebut, Kompilasi Hukum Islam kiranya tidak bisa mengelak kecuali harus menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
KHI dan Konteks Politik Hukum
Telah maklum bahwa KHI lahir bukan dari kondisi yang vakum. Ada kondisi-kondisi sosial, politik, dan hukum yang mendorong KHI harus lahir. KHI lahir dari rahim negara. Ia lahir sebagai produk politik negara Orde Baru, yang jika dipandang dari optik politik hukum tentu saja tidak bebas nilai dan tidak bebas kuasa dari muatan interest politik rezim itu. Dengan perkataan lain, pembidanan kelahiran dan keberadaan KHI terselimuti oleh bias-bias kekuasaan rezim Orde Baru. Setiap legislasi oleh negara, apalagi negara Orde Baru yang saat itu berwatak otoritarian-birokratik, terdapat suatu kehendak-kehendak sosial politik tersembunyi yang menyertainya, sebagaimana anutan banyak pakar hukum bahwa tak ada hukum yang bebas nilai, bebas kepentingan, dan bebas kuasa. Termasuk dalam jaring-jaring ini adalah hukum Islam yang terkumpulkan dalam KHI, kehadirannya menjadi sarat dengan nilai, kepentingan, dan relasi kuasa. Dengan nalar demikian, wajar kiranya kalau KHI dipandang oleh sebagian orang sebagai “fikih madzhab negara”. Ini karena elemen-elemen konstruksi hukum Islam dalam KHI mulai dari inisiatif, proses penelitian, penyusunan, hingga penyimpulan terakhir dari pilihan-pilihan hukumnya semuanya dilakukan oleh suatu tim yang beranggotakan hampir seluruhnya orang-orang negara. Betapa latar belakang pembentukan, logika hukum yang digunakan, hingga pola redaksi yang diterapkan juga sebagaimana lazimnya digunakan oleh hukum positif negara. Bahkan, legitimasi hukum pemberlakuannya juga sangat bergantung pada keputusan negara melalui Instruksi Presiden.
Berdasarkan kajian politik hukum, KHI setidak-tidaknya memiliki 4 (empat) buah karakter hukum yang spesifik sebagai akibat logis dari pengaruh politik hukum pada masanya. Karakter-karakter tersebut adalah sebagai berikut:
[1] dari perspektif strategi pembentukan hukum, KHI berkarakter semi-responsif, yakni proses pembentukannya dikuasai oleh pihak yudikatif (MA) dan eksekutif (Depag RI), sementara pihak legislative (DPR) selaku perwakilan-formal rakyat Indonesia tidak terlibat sama sekali dan perwakilan masyarakat Islam (MUI dan cendekiawan Muslim di IAIN) berada pada posisi peripheral; [2] dari perspektif materi hukum, KHI berkarakter otonom, reduksionistik dan konservatif.
Artinya, materi hukum Islam pada KHI secara substansial diakui sebagai fiqh (yurisprudensi Islam), namun hanya sebagian kecil materi hukum Islam yang dilegislasikan [perkawinan, kewarisan, dan perwakafan] dengan formulasi bahasa dan pokok masalah yang tidak adaptif dan inovatif; [3] dari perspektif implementasi hukum, KHI berkarakter fakultatif, yakni tidak secara a priori harus ditaati dan bisa memaksa setiap warga negara, meski beragama Islam, untuk melaksanakan ketentuan KHI; dan [4] dari perspektif fungsi hukum, KHI berkarakter regulatif dan legitimatif, yakni ketentuan hukumnya lebih bersifat teknis-prosedural dan praktis-operasional ketimbang strategis-konsepsional dan teoritik. Selain itu, aturan-aturan hukumnya cenderung melakukan pembenaran terhadap ketentuan hukum positif sebelumnya dan institusi-institusi bentukan negara, seperti KUA, PPAIW, Pengadilan Agama, dan lain-lain. Walhasil, hukum Islam dalam KHI telah bergeser dari otoritas hukum agama [divine law] menjadi otoritas hukum negara [state law].
KHI dalam Perbandingan Hukum Keluarga Negeri-Negeri Muslim
Kiranya penting juga untuk menjuktaposisikan KHI dengan hukum keluarga (the family law) yang ada di berbagai negeri Islam yang lain. Negeri-negeri Muslim tersebut telah berkali-kali mengadakan sejumlah pembaharuan terhadap hukum keluarga.
TUNISIA
Tunisia adalah sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Tunisia merdeka pada tanggal 20 Maret 1956. Sesaat setelah itu, Pemerintah Tunisia telah membuat undang-undang hukum keluarga yang bernama Majallah al-Ahwâl al-Syakhshiyyah Nomor 66 Tahun 1956. Semenjak ditetapkan, Majallah tersebut telah berkali-kali mengalami perubahan, penambahan, modifikasi, yaitu pada tahun 1959, 1964, 1981, dan 1993. UU tersebut mencakup materi hukum perkawinan, perceraian, dan pemeliharaan anak yang dari segi material berbeda dengan ketetapan fikih klasik. Dari sekian banyak pembaharuan terhadap UU tersebut, pada tahun 1959 telah ditetapkan tentang keharusan perceraian di pengadilan dan larangan untuk berpoligami. Sementara itu, menyangkut anak angkat atau adopsi telah diatur secara khusus dalam UU Perwalian dan Adopsi tahun 1958. UU ini terdiri dari 60 pasal yang dibagi ke dalam 3 bab, yaitu mengenai perwalian umum, kafalah, dan anak angkat. Dalam pasal 9-16, misalnya disebutkan bahwa pihak yang akan mengadopsi anak disyaratkan sudah dewasa, menikah, memiliki hak-hak sipil secara penuh, bermoral baik, sehat jasmani dan rohani, dan secara finansial mampu memenuhi kebutuhan anak yang diadopsi. Selain itu, selisih umur antara pihak yang mengadopsi dan yang diadopsi adalah 15 tahun. Di dalam keluarga angkatnya, anak angkat memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagaimana anak kandung.
SYRIA
Menyangkut hukum keluarga, Syiria telah memiliki Qanûn al-Ahwâl al-Syakhshiyyah tahun 1953. Setelah berlaku selama 22 tahun, undang-undang ini kemudian diamandemen menjadi UU Nomor 34 tahun 1975 dengan maksud untuk menjamin hakhak perempuan dalam pandangan hukum Islam. Sebelum diamademen, berkenaan dengan poligami UU tersebut (pasal 17) menyatakan demikian, “hak poligami bagi suami diperbolehkan asalkan suami dapat membuktikan bahwa ia mampu untuk memberi hidup kepada isteri”. Setelah diamandemen, pasal poligami itu berbunyi, “Pengadilan bisa saja tidak memberikan izin untuk poligami kecuali ada justifikasi hukum untuk poligami dan mampu membiayai dua isteri”. Dengan mempersyaratkan perizinan dari pihak pengadilan, maka sedikitnya telah memperpanjang dan mempersulit proses
poligami. Sementara itu, masalah perceraian merupakan persoalan menarik dalam hukum keluarga Syiria karena terkait dengan hak isteri untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya melalui jalur khulu’. Selain melalui khulu’, isteri dapat pula mengajukan pemutusan hubungan perkawinan kepada pengadilan disebabkan kasuskasus antara lain: suami menderita penyakit yang dapat menghalangi untuk hidup bersama, penyakit gila dari suami, suami meninggalkan isteri atau dipenjara lebih dari tiga tahun, suami dianggap gagal memberikan nafkah, dan penganiayaan suami terhadap isteri.
MESIR
Secara historis, pembaharuan hukum keluarga di Mesir dimulai sekitar tahun 1920. Pada tahun ini, seri pertama rancangan undang-undang hukum keluarga resmi diundangkan. Pada tahun 1929 dilakukan amandemen kedua terhadap beberapa pasal pada undang-undang sebelumnya. Setelah itu, tercatat dua kali amandemen terhadap hukum keluarga Mesir yaitu pada tahun 1979 dan 1985. Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Mesir antara lain terkait dengan masalah poligami, wasiat wajibah, warisan, dan pengasuhan anak. UU Nomor 100 tahun 1985 menyatakan bahwa seorang yang akan menikah harus menjelaskan status perkawinannya pada formulir pencatatan perkawinan. Bagi yang sudah mempunyai isteri, harus mencantumkan nama dan alamat isteri atau isteri isterinya. Pegawai pencatat harus memberitahu isterinya tentang rencana perkawinan tersebut. Seorang isteri yang suaminya menikah lagi dengan perempuan lain dapat minta cerai dengan berdasarkan kemudharatan ekonomi yang diakibatkan poligami dan mengakibatkan tidak mungkin hidup bersama dengan suaminya. Hak isteri untuk minta cerai hilang dengan sendirinya ketika yang bersangkutan tidak memintanya selama satu tahun setelah ia mengetahui perkawinan tersebut. Bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan atau denda 200 Pound Mesir atau kedua-duanya.
YORDANIA
Sampai tahun 1951, Yordania masih memberlakukan hukum keluarga Turki Usmani sampai diundangkannya undang-undang hak-hak keluarga Nomor 92 Tahun 1951. Undang-Undang ini mengatur tentang perkawinan, perceraian, mahar, pemenuhan nafkah bagi isteri dan keluarga, dan tentang pemeliharaan anak. Pada perkembangan berikutnya, UU tersebut telah diganti dengan status personal Yordan 1976 (UU Nomor 61 Tahun 1976) yang disebut dengan Qanûn al-Ahwâl al-Syakhshiyyah. Amandemen berikutnya terjadi pada tahun 1977 yang menghasilkan UU Nomor 25 Tahun 1977. Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Yordania antara lain terkait dengan masalah usia menikah, janji pernikahan, perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan, perceraian, dan wasiat wajibah. Mengenai usia pernikahan dinyatakan bahwa syarat usia perkawinan adalah 17 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Apabila perempuan telah mencapai usia 15 tahun dan mempunyai keinginan untuk menikah sementara walinya tidak mengijinkan tanpa alasan yang sah, maka perempuan tersebut pada dasarnya tidak melanggar prinsip-prinsip kafâ`ah dan pengadilan dapat memberikan ijin pernikahan. Demikian juga apabila perempuan telah mencapai umur 18 tahun dan walinya keberatan memberikan izin tanpa alasan kuat, maka pengadilan dapat memberi izin pernikahan. Sementara itu, janji untuk mengadakan pernikahan diatur pada pasal 2 dan 3 UU Tahun 1951. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa janji menikah tidak akan membawa akibat pada adanya pernikahan. Namun, setelah adanya perjanjian, kemudian salah satunya meninggal atau perjanjian batal, maka beberapa hadiah sebelumnya dapat diambil kembali oleh pihak laki-laki.
IRAK
Irak pernah memiliki Qanûn al-Ahwâl al-Syakhshiyyah yang mengatur masalah keluarga. Undang-undang ini secara resmi diumumkan pada Bulan Desember 1959. Prinsip prinsip tentang masalah keluarga dalam undang-undang ini diambil dari berbagai madzhab dalam Islam yang meliputi Sunni, Syi’ah, dan juga hukum keluarga yang berlaku di beberapa negeri Muslim seperti Mesir, Yordania, dan Syiria. Perundangundangan tersebut kemudian diamandemen pada tahun 1963, 1978, dan 1983. Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Irak antara lain terkait dengan masalah status wali, pemberian mahar, wasiat wajibah, dan pengasuhan anak (hadhânah). Pasal 19-22 mengatur tentang ketentuan pembayaran mahar. Pasal-pasal ini menjelaskan bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan mahar yang ditetapkan secara khusus di dalam perjanjian perkawinan. Jika mahar tidak ditetapkan secara khusus, maka perempuan berhak menerima mahar yang pantas (mahar mitsil). Jika pihak yang lain menggagalkan perkawinan atau meninggal dunia, maka harta yang telah diberikan harus dikembalikan secara utuh. Sementara mengenai masalah pengasuhan anak di atur dalam pasal 57 ayat 1-9. Secara panjang lebar dijelaskan antara lain bahwa ibu memiliki hak istimewa dalam mengasuh dan mendidik anak selama perkawinan berlangsung. Begitu juga setelah perkawinan, dengan catatan ia tidak berbuat aniaya terhadap anak tersebut. Pengasuh tersebut harus dewasa, sehat, dapat dipercaya dan mampu bertanggungjawab dan melindungi anaknya serta tidak kawin lagi dengan lelaki asing.
KHI dalam Lingkup Problematika sosial
Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yang antara lain membawa kepada perubahan pola interaksi manusia, sejumlah problem sosial muncul. Problem-problem ini pada umumnya tidak terwadahi secara memadai dalam KHI. Problem sosial yang dimaksud adalah persoalan ketidakadilan, ketidakmanusiawian, dan diskriminasi yang ditemukan terutama dalam dua materi pokok KHI, yaitu hukum perkawinan dan hukum kewarisan.
Di samping itu, terdapat pula beberapa persoalan yang cukup penting yang belum terakomodasi dalam hukum perwakafan. Pada bidang hukum perkawinan, harus fair diakui bahwa dalam KHI terdapat beberapa pasal yang problematis dari sudut pandang keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Di antara masalah-masalah yang kurang mendukung semangat keadilan tersebut antara lain: batas usia pernikahan, wali nikah, saksi nikah, hak dan kewajiban suami isteri, nusyuz, poligami, dan nikah beda agama. Pasal-pasal yang dinilai sarat dengan ketidakadilan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, batas usia minimal nikah yang diatur dalam pasal 15 ayat (1). Pasal ini dianggap tidak adil karena telah mematok usia minimal perempuan boleh menikah lebih rendah dari usia laki-laki. Pasal ini jelas memperlakukan laki-laki dan perempuan secara diskriminatif, yakni semata-mata didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan laki-laki (ideologi patriarkhis).
Kedua, tentang wali nikah. Pembahasan tentang wali nikah dijelaskan dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Di antara pasal-pasal tersebut, yang cenderung bias jender adalah pasal 19, 20 ayat (1) dan 21 ayat (1). Hak kewalian hanya dimiliki oleh orang yang berkelamin laki-laki. Tidak ada ruang sedikitpun bagi seorang ibu untuk menjadi wali nikah atas anak perempuannya, misalnya ketika sang ayah berhalangan. Sekiranya ayah tidak memungkinkan untuk tampil menjadi wali, maka hak kewalian jatuh pada kakek. Jika kakek ‘udzur, maka hak kewalian tidak secara otomatis pindah ke tangan ibu, tetapi turun pada anak laki-laki atau saudara laki-laki kandung dari si perempuan tersebut. Hirarki kewalian ini telah diatur oleh KHI dalam pasal 21 dengan menutup sama sekali peluang perempuan untuk menjadi wali. Untuk itu, secara praktis harus ditegaskan bahwa pasal tentang perwalian dalam KHI hendaknya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki memiliki otoritas untuk menikahkan dirinya sendiri dan berwenang menjadi wali nikah, maka seharusnya demikian juga untuk perempuan.
Ketiga, tentang saksi. Ketentuan tentang saksi dalam pernikahan diatur dalam pasal 24,25, dan 26. Namun, yang dinilai bias jender hanyalah pasal 25 saja yang menutup sama sekali kemungkinan perempuan untuk menjadi saksi pernikahan. Dengan menggunakan parameter kesetaraan gender, maka semestinya laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk tampil sebagai saksi nikah.
Keempat, kepala rumah tangga hanya disandangkan pada pundak seorang suami, dan tidak pada isteri. Pasal 79 KHI mengatakan suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Sebagaimana fikih pada umumnya, KHI tidak pernah mempertimbangan kapabilitas dan kredibilitas isteri untuk memangku status kepala keluarga. Jabatan “kepala keluarga” telah diberikan secara gratis dan otomatis kepada para suami.
Kelima, pengaturan tentang nusyûz dalam KHI terdapat dalam pasal 84 ayat (1). Namun demikian, dalam persoalan nusyûz ini KHI masih terlihat bias jender. Sebab, masalah nusyûz dalam KHI hanya berlaku bagi pihak perempuan, sementara laki-laki (baca: suami) yang mangkir dari tanggungjawabnya tidak diatur dan tidak dianggap nusyûz. Oleh sebab itu, pasal ini terlihat mengekang kebebasan hak-hak perempuan dan tidak mendudukkan hubungan suami isteri secara setara.
Keenam, pemberian mahar dari seorang suami terhadap isteri. Pertanyaannya, bukankah dengan mahar ini, laki-laki (suami) semakin digdaya di hadapan perempuan (isteri). Terdapat anggapan yang menggumpal di alam bawah sadar seorang suami bahwa dirinya telah “membeli” (alat kelamin, vagina) isteri, sehingga dapat dengan leluasa memperlakukannya. Transaksi “pembelian” melalui selubung mahar ini akan terungkap dengan jelas ketika membaca pasal 35 ayat 1 yang berbunyi, “suami yang mentalak isterinya qabla al-dukhûl wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Dalam fikih, walau masih diperdebatkan, ada pendapat yang menyatakan bahwa hak suami terhadap isteri adalah haqq al-tamlîk dan bukan haq al-intifâ.
Ketujuh, poligami. Dalam KHI poligami masih dimungkinkan untuk dilakukan. Pandangan ini seperti ini dapat disangkal dengan dua alasan berikut: [1] asas perkawinan dalam Islam adalah monogami dan bukan poligami. Oleh karena itu, perkawinan poligami jelas bertentangan dengan asas tersebut. [2] Perkawinan poligami dalam prakteknya sangat menyakitkan bagi istri. Beberapa penelitian menemukan sebuah fakta bahwa sebagian besar perkawinan poligami diselenggarakan secara sembunyisembunyi tanpa sepengetahuan dan seijin istri. Dengan fakta ini, maka tindak kebohongan yang begitu menyakitkan telah terjadi. Kejujuran dan keterbukaan yang semestinya menjadi landasan utama dalam rumah tangga kemudian menjadi rapuh.
Kedelapan, nikah beda agama. Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi sepasang pemuda dan pemudi yang hendak melangsungkan suatu perkawinan. Artinya, orang Islam baik laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang non-Islam. Pandangan seperti ini tentu saja bertentangan prinsip dasar ajaran Islam, yaitu pluralisme. Dengan berlandas tumpu pada nalar pluralisme itu, maka tidak tepat menjadikan perbedaan agama (ikhtilâf ad-dîn) sebagai penghalang (mâni’) bagi dilangsungkannya suatu perkawinan beda agama. Selain ketidakadilan pada hukum perkawinan, KHI juga tidak mencerminkan keadilan pada hukum kewarisan. Dalam hukum kewarisan, ketentuan-ketentuan hukum KHI tampak mengabaikan hak-hak anak yang sedang dalam kandungan. KHI hanya memperhitungkan bagian anak yang telah lahir. Padahal, anak yang sedang dalam kandungan justru memiliki beban yang lebih berat, baik dari aspek psikologis maupun finansial. Oleh karena itu, sudah selayaknya KHI merumuskan konsep tentang pembagian warisan bagi anak yang sedang dalam kandungan.
Ketidakadilan lain terlihat pada pasal 172 KHI yang diantaranya menyatakan bahwa bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Secara implisit, pasal ini menyatakan bahwa agama ibu tidak bernilai sama sekali pada anaknya, baik dalam pandangan masyarakat maupun dalam pandangan Tuhan. Padahal, posisi ibu dalam keluarga sangat penting sebagai pendidik dan perambah masa depan anak-anaknya. Ini tidak saja mengabaikan peran dan posisi ibu dalam keluarga dan amsyarakat, tetapi juga menafikan agama yang dianut ibu di hadapan anak-anaknya.
Hal senada juga terjadi pada pasal 186 KHI. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan kelaurga dari pihak ibunya. Sementara status anak yang lahir karena kawin sirri tidak diatur dalam kaitan dengan hubungan kewarisan. Oleh karena itu, definisi sah atau tidaknya perkawinan kiranya penting untuk ditinjau kembali.
Di samping nuansa ketidakadilan, hukum kewarisan juga memuat beberapa kendala teknis yang dirasakan sulit dalam penerapannya. Kendala teknis itu, antara lain, terdapat pada pasal 192 dan 193 yang tidak menjelaskan secara eksplisit mana yang ‘awl dan mana pula yang radd. Jika tidak segera dijelaskan tentu saja akan menyulitkan para hakim di pengadilan untuk menyelesaikan persoalan warisan keluarga Muslim. Kendala teknis lain terdapat pada Bab V dan bab VI yang tidak menjelaskan secara rinci definisi wasiat dan hibah. Pendefinisian dua terminologi ini cukup penting karena adanya kemiripan dalam praktik wasiat dan hibah.
Sedangkan dari sisi hukum wakaf, KHI juga belum dapat dikatakan sempurna mengingat masih banyak persoalan penting yang belum terakomodasi. Di antara persoalan tersebut adalah ketentuan wakaf non-Muslim perlu mendapat tempat dalam KHI mengingat adanya beberapa kasus yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya hal tersebut. Aturan itu setidaknya dapat menegaskan boleh tidaknya warga non-Muslim untuk mewakafkan harta bendanya untuk kepentingan umat Islam. Aturan tentang wakaf tunai juga perlu diakomodasikan dalam KHI.
Hal ini karena perkembangan dunia perbankan syarî’ah yang cukup pesat, sehingga visi dan perspektif manusia dalam “menginvestasikan” hartanya di jalan Allah juga berubah. Sebagai contoh, aturan tentang seseorang atau sekelompok orang ataupun suatu badan usaha yang bermaksud mewakafkan uangnya dalam bentuk deposito, kemudian keuntungan bagi hasil deposito tersebut dimanfaatkan untuk membantu para korban bencana alam ataupun untuk membiayai pendidikan masyarakat miskin. Wakaf dalam bentuk ini tentu saja sangat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan utama wakaf dalam Islam.
KHI dan Problem Metodologis (Ushul Fiqh).
KHI dan Problem Metodologis (Ushul Fiqh).
Dalam banyak kajian akademis, KHI tidak digali sepenuhnya dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan banyak “mengangkut” begitu saja penjelasan normatif tafsirtafsir keagamaan klasik, dan kurang mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat Islam Indonesia. KHI mengutip nyaris sempurna seluruh pandangan-pandangan fikih “purba”. KHI tidak betul-betul merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam Indonesia, akibat tidak digali secara seksama dari kearifan-kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendeknya, telah terjadi sakralisasi fikih klasik yang kita yakini para penulisnya sendiri tidak menginginkan hal itu.
Sejumlah pemikir Islam telah menilai beberapa sisi ketidakrelevanan fikih-fikih klasik itu, oleh karena ia memang disusun dalam era, kultur dan imajinasi sosial yang berbeda. Bahkan, disinyalir bahwa fikih klasik tersebut bukan saja tidak relevan dari sudut materialnya, melainkan juga bermasalah dari ranah metodologisnya. Misalnya, per definisi fikih selalu dipahami sebagai “mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil tafshili, yaitu al-Qur`an dan al-Sunnah” [al-‘ilmu bi al-ahkâm al-syar’iyyah al-‘amaliyyah al-muktasab min adillatihâ al-tafshîliyyah]. Mengacu pada ta’rîf tersebut, kebenaran fikih menjadi sangat normatif, sehingga kebenaran fikih bukan dimatriks dari seberapa jauh ia memantulkan kemaslahtan bagi umat manusia, melainkan pada seberapa jauh ia benar dari aspek perujukannya pada aksara al-Qur`an dan al-Sunnah.
Metodologi dan pandangan literalistik ini belakangan terus mendapatkan pengukuhan dari kalangan Islam fundamentalis-idealis. Mereka selalu berupaya untuk menundukkan realitas ke dalam kebenaran dogmatik nash, dengan pengabaian yang nyaris sempurna terhadap kenyataan konkret di lapangan. Bahkan, seringkali terjadi, mereka telah melakukan tindakan eisegese, yakni membawa masuk pikiran atau ideologinya sendiri ke dalam nash, lalu menariknya ke luar dan mengklaimnya sebagai maksud Tuhan. Klaim kebenaran ini sangat berbahaya. Ia hanya akan membuat umat Islam menjadi semakin eksklusif dalam tata pergaulan yang multireligius dan multikultural. Telah terbukti, klaim-klaim seperti itu tidak memberikan pengaruh positif apapun dalam usaha-usaha membangun kehidupan bersama yang toleran dalam masyarakat yang mejemuk.
Kesalahan epistemologis semacam inilah yang menjadi utang besar model literalistik. Untuk menghindari kegawatan itu, hal-hal berikut perlu mendapatkan perhatian utama. Pertama, mengungkapkan dan merevitalisasi kaidah ushul marginal yang tidak terliput secara memadai dalam sejumlah kitab ushul fikih. Terus terang, walau kerap muncul dalam kitab-kitab ushul fikih, kaidah-kaidah berikut belum difungsikan secara optimal, seperti [1] al-‘ibrah bi khushûsh al-sabab lâ bi ‘umûm al-lafadz. Kaidah ini hendak mengatakan bahwa sebuah pemikiran atau pernyataan selalu memiliki latar subyektifnya sendiri. Dengan demikian, generalisasi dan idealisasi tanpa batas harus dihindari; [2] takhshîsh bi al-‘aql wa takhshîsh bi al-‘urf. Bahwa akal dan tradisi memiliki kewenangan untuk mentakhshîsh suatu nash agama; [3] al-amr idzâ dlâqa ittasa’a. Ini penting direvitalisasi, karena umat Islam over dosis memakai kaidah kebalikannya: al-amr idzâ ittasa’a dhâqa, dan sebagainya. Kedua, sekiranya usaha pertama tidak lagi memadai untuk menangani dan menyelesaikan problem-problem kemanusiaan, maka upaya selanjutnya adalah membongkar bangunan paradigma ushul fikih lama; [1] mengubah paradigma dari teosentrisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis; [2] bergerak dari eisegese ke exegese. Dengan exegese, para penafsir berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan nash sebagai “obyek” dan dirinya sebagai “subyek” dalam suatu dialektika yang seimbang. [3] Memfikihkan syari’at atau merelatifkan syari’at. Syari’at harus diposisikan sebagai jalan (wasîlah, hâjiyat) yang berguna bagi tercapainya prinsipprinsip Islam (ghâyat, dlarûriyat) berupa keadilan, persamaan, kemaslahatan, penegakan HAM. Dus, shalat, zakat, puasa, haji adalah wasîlah dan bukan ghâyah-dlarûriyat. [4] Kemaslahatan sebagai rujukan dari seluruh kerja penafsiran. [5] Mengubah gaya berfikir deduktif ke induktif (istiqrâ`iy). Di sinilah letak pentingnya KHI menimba sebanyak-banyaknya dari kearifan-kearifan lokal (local wisdom, al-‘urf).
Dari fondasi paradigmatik ini kita dapat merencanakan beberapa kaidah ushul fikih alternatif, misalnya, pertama, adalah kaidah al-ibrah bi al-maqâshid la bi al alfadz. Kaidah ini berarti bahwa yang mesti menjadi perhatian seorang mujtahid di dalam mengistinbatkan hukum dari al-Qur`an dan al-Sunnah bukan huruf dan aksaran al- Qur`an dan al-Hadits melainkan dari maqâshid yang dikandungnya. Yang menjadi aksis adalah cita-cita etik-moral dari sebuah ayat dan bukan legislasi spesifik atau formulasi literalnya. Nah, untuk mengetahui maqâshid ini maka seseorang dituntut untuk memahami konteks. Yang dimaksudkan bukan hanya konteks personal yang juz`iy-partikular melainkan juga konteks impersonal yang kulli-universal. Pemahaman tentang konteks yang lebih dari sekadar ilmu sabab al-nuzul dalam pengertian klasik itu merupakan prasyarat utama untuk menemukan maqâshid al-syarî’ah. Kedua, adalah kaidah jawaz naskh al-nushush bi al maslahah.
Bahwa menganulir ketentuan-ketentuan ajaran dengan menggunakan logika kemaslahatan adalah diperbolehkan. Kaidah ini sengaja ditetapkan, oleh karena syari’at (hukum) Islam memang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (jalb almashalih), dan menolak segala bentuk kemafsadatan (dar`u al-mafasid). Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, seorang tokoh Islam bermadzhab Hanbali, menyimpulkan bahwa syari’at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan (al-hikmah). Prinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran para ahli fikih ketika memutuskan suatu kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam.
Ketiga, adalah kaidah tanqih al nuhush bi al-‘aql al-mujtama’. Kaidah ini hendak menyatakan bahwa akal publik memiliki kewenangan untuk menyulih dan mengamandemen sejumlah ketentuan “dogmatik” agama menyangkut perkaraperkara publik. Sehingga ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan bunyi harfiah teks ajaran, maka akal publik berotoritas untuk mengedit, menyempurnakan, dan memodifikasikannya.
Modifikasi ini terasa sangat dibutuhkan ketika berhadapan dengan ayat-ayat partikular, seperti ayat poligami, nikah beda agama, iddah, waris beda agama, dan sebagainya. Ayat-ayat tersebut dalam konteks sekarang, alih-alih bisa menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan, yang terjadi bisa-bisa merupakan
bagian dari masalah yang harus dipecahkan melalui prosedur tanqih yang berupa taqyid bi al-‘aql, takhshish bi al-‘aql, dan tabyin bi al-‘aql.
bagian dari masalah yang harus dipecahkan melalui prosedur tanqih yang berupa taqyid bi al-‘aql, takhshish bi al-‘aql, dan tabyin bi al-‘aql.
Menyusun Visi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia
Bertolak dari beberapa problem di atas, maka ke depan KHI diharapkan dapat mencerminkan visi dan landasan berikut:
1. Pluralisme (al-Ta’addudiyyah).
Tak terbantahkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat plural. Pluralitas initerjadi bukan hanya dari sudut etnis, ras, budaya, dan bahasa melainkan juga agama. Sehingga, kemajemukan di Indonesia tidak mungkin bisa dihindari. Keberagaman telah menyusup dan menyangkut dalam pelbagai ruang kehidupan. Tidak saja dalam ruang lingkup keluarga besar seperti masyarakat negara, bahkan dalam lingkup keluarga, pluralitas juga bisa berlangsung. Setiap orang senantiasa berada dalam dunia pluralitas.
Menghadapi pluralitas tersebut, yang dibutuhkan tentu saja bukan pada bagaimana menjauhkan diri dari kenyataan pluralisme tersebut, tetapi pada bagaimana cara dan mekanisme yang bisa diambil di dalam menyikapi pluralitas itu. Sikap antipati terhadap pluralitas, di samping bukan merupakan tindakan yang cukup tepat, juga akan berdampak kontra-produktif bagi tatanan kehidupan manusia yang damai.
2. Nasionalitas (Muwâthanah).
Telah maklum bahwa sebagai sebuah negara, Indonesia dibangun bukan oleh satu komunitas agama saja. Indonesia merekrut anggotanya bukan didasarkan pada kriteria keagamaan, tetapi pada nasionalitas. Dengan perkataan lain, yang menemalikan seluruh warga negara Indonesia bukanlah basis keagamaan, melainkan basis nasionalitas (muwâthanah). Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil jerih payah seluruh warga bangsa, bukan hanya masyarakat Islam melainkan juga non Islam, bukan hanya masyarakat Jawa melainkan juga masyarakat luar Jawa.
Dengan nalar demikian, Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas dua. Umat non-Islam Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai dzimmi atau ahl al-dzimmah dalam pengertian fikih politik Islam klasik. Oleh karena itu, menjadikan nasionalitas sebagai aksis atau poros di dalam perumusan hukum Islam khas Indonesia adalah niscaya. Artinya, kenyataan nasionalitas Indonesia mestinya merupakan batu pijak dari hukum Islam. Ini penting dilakukan. Sebab, sebagai agama mayoritas, Islam (dan segala urusan yang berkaitan dengannya) tidak pernah menjadi urusan umat Islam sendiri. Apa yang terjadi pada Islam dan umatnya kerap membawa dampak yang besar buat orang lain (al-akhar). Tentu, upaya ini tidak gampang dilakukan di tengah kecenderungan untuk menghidupkan secara terus-menerus hukum (fikih) Islam klasik. Akan tetapi, tetaplah harus diupayakan bahwa realitas pluralisme merupakan faktor determinan di dalam memformat hukum Islam Indonesia. Penafian terhadap realitas tersebut hanya akan menyebabkan hukum Islam yang dibentuk akan mengalami “miskram” atau keguguran sejak awal.
3. Penegakan HAM (Iqâmat al-Huqûq al-Insâniyyah).
Hak asasi manusia dimaksudkan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia karena terberikan kepadanya. Hak asasi mengungkapkan segi-segi kemanusiaan yang perlu dilindungi dan dijamin dalam rangka memartabatkan dan menghormati eksistensi manusia secara utuh. Oleh karena manusia dengan martabatnya merupakan ciptaan Allah, maka dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia dimiliki manusia karena diberikan oleh Allah sendiri. Dengan demikian, hak asasi manusia secara otomatis akan dimiliki oleh setiap insan yang lahir di bumi ini.
Islam adalah agama yang memiliki komitmen dan perhatian cukup kuat bagi tegaknya hak asasi manusia di tengah masyarakat. Dalam sejarahnya yang awal, Islam hadir justru untuk menegakkan hak asasi manusia, terutama hak kaum mustadh’afîn, yang banyak dirampas oleh para penguasa. Misalnya, Islam datang untuk mengembalikan hak-hak kaum perempuan, para budak, dan kaum miskin. Mereka inilah kelompokkelompok yang rentan kehilangan haknya yang paling asasi sekalipun. Dalam Islam, ada sejumlah hak asasi manusia yang harus diusahakan pemenuhannya, baik oleh diri sendiri maupun negara. Masing-masing adalah hak hidup (hifdz al-nafs aw al-hayât), hak kebebasan beragama (hifdz al-dîn), hak kebebasan berfikir (hifdz al-‘aql), hak properti (hifdz al-mâl), hak untuk mempertahankan nama baik (hifdz al-‘irdh), dan hak untuk memiliki garis keturunan (hifdz al-nasl). Menurut al-Ghazali, pada komitmen untuk melindungi hak-hak kemanusiaan inilah, seluruh ketentuan hukum dalam Islam diacukan.
4. Demokratis.
Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik, secara mendasar bisa dikatakan paralel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Artinya, pada dataran prinsipil tersebut antara Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan. Sejumlah konsep ajaran Islam yang dipandang sejalan dengan prinsip demokrasi adalah; pertama, al-musâwah (egalitarianism). Bahwa manusia memiliki derajat dan posisi yang setara di hadapan Allah. Kedua, al-hurriyah (kemerdekaan). Ketiga, al-ukhuwwah (persaudaraan). Keempat, al-‘adâlah (keadilan) yang berintikan pada pemenuhan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat-negara. Kelima, al-syûra (musyawarah). Bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartsipasi di dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama.
Kiranya mekanisme penyusunan sebuah kompilasi hukum Islam harus bersendikan kelima pokok ajaran tersebut.
5. Kemaslahatan (al-mashlahat).
Sesungguhnya syari’at (hukum) Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (jalb al-mashâlih) dan menolak segala bentuk kemafsadatan (dar`u al-mafâsid). Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, seorang tokoh Islam bermadzhab Hanbali, menyimpulkan bahwa syari’at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan (al-mashlahat), keadilan (al-’adl), kerahmatan (al-rahmat), dan kebijaksanaan (al-hikmah). Prinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran para ahli fikih ketika memutuskan suatu kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsipini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam. Persoalannya, jika acuan hukum adalah kemaslahatan, maka siapa yang berhak mendefinisikan dan yang memiliki otoritas untuk merumuskannya. Untuk menjawabnya, perlu kiranya dibedakan antara kemaslahatan yang bersifat individualsubyektif dan kemashlahatan yang bersifat sosial-obyektif. Yang pertama adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang per orang yang terpisah dengan kepentingan orang lain. Tentu saja sebagai penentu kemaslahatan pertama ini adalah yang bersangkutan itu sendiri, seperti dalam kasus poligami (perempuanlah penentu kemaslahatan dan keadilan).
Sedangkan jenis kemaslahatan kedua adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, otoritas yang memberikan penilaian adalah orang banyak juga melalui mekanisme syûra untuk mencapai konsensus (ijmâ’). Dan sesuatu yang telah menjadi konsensus dari proses pendefinisian maslahat melalui musyawarah itulah hukum tertinggi yang mengikat kita. Di sinilah pemecahan masalah bersama cukup menentukan. Al-Qur`an mengatakan, urusan mereka dimusyawarahkan (dibicarakan dan diputuskan) bersama di antara mereka sendiri. (QS.: al-Syûrâ, 38).
6. Kesetaraan Gender (al-‘Musâwah al-Jinsiyyah).
Gender dan seks merupakan dua entitas yang berbeda. Jika gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosialbudaya, maka seks secara umum dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Artinya, gender bukan kategori biologis yang berkaitan dengan hitungan kromosom, pola genetik, struktur genital, melainkan merupakan konstruksi sosial dan budaya. Sementara seks merupakan kodrat Tuhan bersifat permanen.
Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang perlu dipersoalkan. Tidak mengapa bahwa karena kodratnya, perempuan harus melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Problem baru muncul tatkala perbedaan jenis kelamin tersebut melahirkan ketidakadilan perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan diposisikan sebagai makhluk yang hanya boleh bekerja dalam dunia domestik dan tidak dalam dunia publik karena dunia publik merupakan area khusus bagi laki-laki. Perempuan tidak memiliki kewenangan untuk menjadi pemimpin di tingkat keluarga maupun masyarakat.
Di sinilah letak pentingnya memisahkan seks dan gender secara proporsional. Dari sudut gender, relasi antara laki-laki dan perempuan mesti diletakkan dalam konteks kesetaraan dan keadilan. Sebab, ketidakadilan gender di samping bertentangan dengan spirit Islam, juga hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan. Islam dengan sangat tegas telah mengatakan bahwa laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Yang membedakan di antara mereka hanyalah kadar ketakwaannya saja.
Al-Qur`an tidak menekankan superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin. Hukum Islam mutlak memegangi prinsip ini, sebab kesetaraan gender merupakan unit inti dalam relasi keadilan sosial. Tanpa kesetaran gender tidak mungkin keadilan sosial dapat tercipta. Di sinilah, persoalan konstruksi sosial hukum Islam karena hukum Islam yang kita pahami, yakini, dan amalkan sehari-hari dilahirkan oleh masyarakat dan budaya patriarkhis di mana laki-laki selalu menjadi pusat kuasa, dan misoginis (kebencian terhadap perempuan) sering dianggap wajar dalam penafsiran. Adalah benar belaka bahwa merekonstruksi hukum Islam (fiqh) dewasa ini tidak cukup sekadar melakukan tafsir ulang, tetapi harus melalui proses dekonstruksi (pembongkaran) terhadap bebatuan ideologi yang melilitnya berabad-abad.
Pokok-pokok pikiran ini adalah dasar dan acuan dari kerja pembaharuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Semoga berguna dan bermanfaat. In urîdu illa al-ishlâh mastatha’tu. Wa mâ tawfîqiy illâ billâh.@
****
Jumat, 04 Februari 2011
//
Label:
Fakultas Syariah
//
0
komentar
//
0 komentar to "Menuju Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang Adil Gender"
Diberdayakan oleh Blogger.
Mengenai Saya
Label
- ASWAJA (2)
- Celoteh Syariah (3)
- Fakultas Syariah (8)
- Fiqh (5)
- Puisi (2)
- Radar Syariah (1)
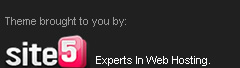









Posting Komentar